Pilkada Tanpa Pilihan: Demokrasi atau Sekadar Administrasi?
Oleh: Wartawan sok Politik
Sudah lama rasanya saya tidak menulis cerita panjang di media online. Terakhir kali, mungkin saat kegaduhan politik sedang mencapai puncaknya—dan jujur saja, setelah itu saya mulai merasa bahwa banyak hal yang perlu dipikirkan lebih dalam, bukan hanya sekadar memenuhi kolom berita dengan kisah-kisah yang cepat dan terburu-buru.
Akhirnya, saya memilih mundur sejenak, memberi diri saya sedikit ruang untuk berpikir. Tapi, entah kenapa, sore kemarin, di kedai kopi kecil yang saya kunjungi, saya merasa ada sesuatu yang harus ditulis, sesuatu yang tak bisa saya abaikan begitu saja.
Di tengah secangkir kopi hitam yang mulai dingin, saya membuka aplikasi berita di ponsel saya. Mata saya langsung tertuju pada headline yang cukup mengejutkan: “Pilkada Tak Ada Kotak Kosong”. Saya menatap kalimat itu sebentar, memikirkannya dengan serius.
Tanpa kotak kosong? Berarti, hanya ada satu pasangan calon yang sudah dipastikan menang, bahkan sebelum suara pertama dihitung? Di mana letak demokrasi dalam sistem seperti ini?
Kopi saya semakin dingin, tapi saya terus membaca.
Pilkada kali ini, di daerah yang saya baca, tampaknya lebih mirip dengan formalitas administratif daripada sebuah ajang kompetisi politik. Tidak ada alternatif lain selain satu pasangan calon yang sudah “dikonfirmasi” sebagai pemenang. Tak ada kotak kosong yang bisa dipilih oleh rakyat yang tidak setuju dengan pilihan yang sudah disiapkan. Pilihan? Sepertinya itu sudah tidak lagi relevan.
Sambil merenung, saya mulai berpikir, apakah ini yang disebut demokrasi? Atau lebih tepatnya, apakah ini yang dulu kita perjuangkan sebagai demokrasi? Bukankah demokrasi seharusnya memberi kita kesempatan untuk memilih—untuk menilai siapa yang pantas memimpin, untuk memberi kita ruang untuk memilih calon yang kita percayai? Tanpa pilihan, saya mulai merasa bahwa Pilkada ini hanyalah formalitas belaka.
Mungkin suatu saat nanti, kita tidak perlu lagi mendatangi TPS. Cukup pilih dari daftar calon yang sudah “disetujui,” kirimkan suara kosong sebagai tanda “dukungan” terhadap sistem yang lebih “efisien” ini, dan selesai.
Semua berjalan lebih cepat, tanpa perlu repot-repot memilih. Bahkan proses pemilihan itu sendiri bisa menjadi kenangan masa lalu—kenangan tentang bagaimana kita dulu masih memiliki kesempatan untuk menentukan nasib daerah kita. Tetapi saat itulah saya sadar, Pilkada yang sebenarnya adalah tentang pilihan, bukan hanya tentang siapa yang sudah dipilihkan untuk kita.
Demokrasi bukan tentang siapa yang sudah pasti menang sebelum kita memilih, tetapi tentang memberi kita ruang untuk memilih, bahkan jika pilihan itu sulit. Demokrasi adalah tentang memberi kita kesempatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan kita jika memang ada yang tidak sesuai dengan hati nurani kita.
Jika Pilkada seperti ini terus berlanjut, maka yang tersisa bukanlah demokrasi, melainkan sebuah prosedur administratif yang harus dilalui, tanpa makna. Kita hanya akan menjadi figur yang mengikuti acara yang sudah ditentukan dari awal, tanpa benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Tanpa pilihan, kita tidak lagi menjadi peserta dalam sistem, kita hanyalah penonton yang tidak memiliki suara.
Saya duduk diam di kedai kopi, merenung sejenak. Kopi saya sudah hampir habis. Tertinggal hanya sedikit sisa yang pahit. Saya sadar bahwa tanpa pilihan, Pilkada hanyalah formalitas—bukan sebuah ajang bagi rakyat untuk menentukan arah daerah mereka. Tanpa pilihan, suara kita tidak lebih dari tanda tangan di kertas yang sudah diisi sebelumnya.
Selesai. Mood menulis saya cukup di sini saja. Kalau masih ada yang bingung, mungkin Pilkada berikutnya kita bisa pilih “Gak Usah Milih,” biar lebih jelas dan nggak buang-buang waktu.
(***)





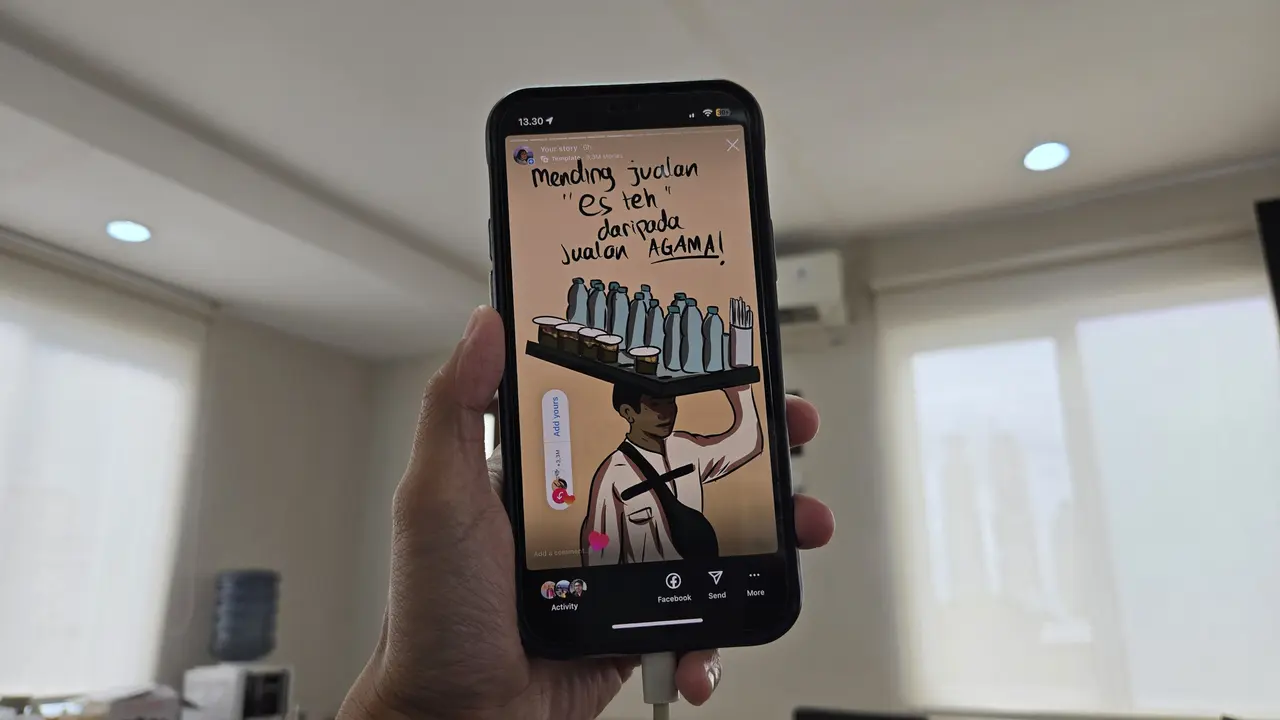


Tinggalkan Balasan